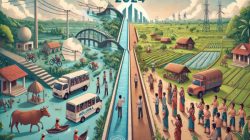BLORANEWS – Demokrasi lahir untuk mengatur kekuasaan yang menjamin adanya kebebasan, kesederajatan dan keadilan bagi warga negara dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dan hak asasinya sebagai manusia. Pelembagaan demokrasi sebagai sebuah sistem tidak hanya menyasar dimensi politik semata. Tetapi juga dimensi ekonomi, hukum, kebudayaan, sosial lingkungan dan tata nilai lain yang berkembang di masyarakat. Semua dimensi tersebut sekalipun secara kelembagaan bisa berdiri sendiri, tetapi karena semua berkaitan dengan kehendak bagi terjaminnya kebebasan, kesederajatan dan keadilan, maka dalam pelaksanaannya selalu berkaitan satu sama lain.
Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara dalam menjalankan kekuasaannya harus dibatasi dengan sistem yang demokratik. Seperti halnya pergantiannya diatur dalam pemilu yang periodik. Tidak bisa misalnya jika politik telah berproses secara demokratik tetapi pengelolaan ekonomi menjadi kapitalistik di tangan para pemilik modal ataupun monopolistik sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat feodal. Sehingga intervensi kekuasaan terhadap proses demokrasi, misalnya dalam pemilu secara nilai sulit ditolerir.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe dalam proses politik menjelang pemilu seketika meletupkan diskursus tidak hanya dalam perspektif politik dalam arti sempit saja. Tetapi juga melebar ke dimensi komunikasi politik, antropologi politik dan menambah perbendaharaan ingatan publik terhadap gaya khas Presiden Jokowi dalam membuat pernyataan-pernyataan di ruang publik yang seringkali tidak bisa dipahami tanpa memandangnya dari sisi kulturnya sebagai seorang Jawa.
Sehingga sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu kekhasan soal komunikasi masyarakat Jawa sambil meletakkannya bersamaan dengan predikat lain yang melekat pada diri Presiden Jokowi sebagai makhluk politik, zoon politicon. Variabel-variabel ini penting karena konteks peristiwa dalam kata cawe-cawe itu adalah peristiwa pemilu.
Menurut Supadjar, peradaban masyarakat Jawa pada umumnya didukung oleh kemampuan berkomunikasi yang berkaitan dengan aspek interaksi sosial. Pergaulan orang Jawa dalam skala lokal, nasional, maupun internasional selalu memerlukan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai.
Dalam budaya Jawa, dikenal adanya unggah ungguh ing basa, kasar alusing rasa dan juga genturing tapa. Ungkapan tersebut menghendaki keselarasan hidup, lahir batin, jasmani rohani dan material spiritual, membuat deskripsi yang berkaitan dengan kata kerja dalam bahasa Jawa. Penggunaan kata kerja dalam komunikasi mesti memperhatikan tata krama. Cara berkomunikasi harus memperhatikan konversi bahasa dengan konteks yang ada sehingga selalu ada jarak antara apa yang diucapkan sesuai perbendaharaan kata yang dimilikinya dengan dengan tindakan yang dilakukan baik itu belum terjadi, sedang terjadi maupun sudah terjadi.
Presiden Joko Widodo adalah salah satu figur dengan banyak predikat yang melekat padanya. Mulai dari sebagai individu politisi, petugas partai, seorang ayah dari sebuah keluarga – memiliki anak dan menantu yang terjun dalam dunia politik – juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Maka cawe-cawe yang dimaksudkan tentu dalam kapsitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tentu saja, termasuk dengan sebagaian perangkat yang digunakan jika cawe-cawe itu dilakukan berkaitan dengan apa yang ada dalam genggaman kekuasaannya.
Publik bisa menyimpulkan sendiri apakah cawe-cawe itu sebagai sebuah rencana atau justru sudah dan akan terus terjadi dalam konteks pemilu sebagai sebuah prosedur demokrasi.
Trauma Historis Intervensi Politik
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokratik dalam tataran prosedural. Pemilu menjadi pintu masuk menuju kekuasaan. Sehingga pemilu menjadi setengah hal paling penting dari keseluruhan proses demokrasi. Karena itulah, maka sekalipun pemilu merupakan peristiwa politik, tetapi intervensi non politik sangat kental. Dalam bentuknya yang paling sempurna, intervensi tersebut menjadikan pemilu sebagai ritual formalitas demokrasi. Sehingga apa yang dihasilkannya secara kelembagaan belum tentu bahkan tidak mencerminkan kehendak publik.
Peristiwa semacam itu sangat kental mewarnai perjalanan sejarah politik Bangsa Indonesia, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Gejala politik yang tidak sehat mewarnai perjalanan politik vis a vis proses pemilunya juga. Kita pernah mengalami trauma demokratik dengan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur hidup. Kita juga mempunyai trauma demokratik yang sama dengan sistem politik pada masa Orde Baru yang proses politik – termasuk pemilu didalamnnya – serta lembaga-lembaga politik yang hidup pada masanya hanya menjadi stempel saja bagi kekuasaan eksekutif.
Demokrasi dan pemilu ala kedua masa tersebut merupakan contoh historis dua model praktik demokrasi dengan dominasi kepemimpinan. Seperti masa Orde lama yang terkenal dengan Demokrasi terpimpinnya, serta pada masa Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila ala Orba yang menyembunyikan watak otoriternya dengan menerapkan Azas Tunggal Kepartaian, Monoloyalitas PNS dan TNI/POLRI, serta Otoritarianisme Birokrasi.
Miriam Budiarjo berpendapat bahwa Soekarno menginginkan suatu konsep demokrasi ala Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong dibawah tuntunan seorang pemimpin. Salah satu gagasan Soekarno yang lain yaitu penguburan partai-partai politik yang disampaikan dalam pidatonya di muka pertemuan delegasi pemuda dari semua partai dan di muka semua persatuan guru-guru pada tahun 1956. Pada saat itu, Soekarno menyatakan bahwa tak seorangpun dapat membenarkan adanya 40 buah partai di negeri ini, dia juga mengajak untuk mengubur partai-partai.
Soekarno tidak suka pada sistem multi partai karena terlalu banyak partai malah menimbulkan ketidakstabilan di kabinet dan parlemen. Sebenarnya, Soekarno lebih menginginkan terbentuknya satu partai tunggal atau partai pelopor pada awal kemerdekaan. Tetapi hal itu tidak mendapatkan persetujuan dari KNIP karena dikhawatirkan menjadi pesaing KNIP. Ditambah munculnya maklumat pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik membuat usulan Soekarno menjadi gagal.
Pada pidatonya tertanggal 21 Febuari 1957 dengan Judul “Menyelamatkan Republik Proklamasi”, Soekarno mengeluarkan gagasan yang disebut konsepsi presiden. Soekarno menyatakan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer menunjukkan bahwa demokrasi tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Demokrasi tersebut adalah demokrasi Import yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sehingga kita mengalami ekses-ekses dalam penyelenggaraannya.
Usaha Presiden Soekarno untuk menyederhanakam sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Perpres No. 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945, diganti dengan partai-partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diakui pemerintah. Hanya 10 partai yang memenuhi syarat tersebut. Yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti. Sedangkan partai lain tidak memenuhi syarat, termasuk PSI dan Masyumi yang dituduh terlibat pemberontakan PRRI/PERMESTA (Budiardjo, 1998).
Guna mewadahi 10 partai tersebut, maka dibentuklah Front Nasional yang berdasarkan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) ditambah golongan fungsional termasuk militer. PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya untuk melemahkan kedudukan partai politik. Tetapi akibatnya dalam perpolitikan nasional malah terjadi persaingan baru dan sebuah segitiga kekuatan politik. Yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.
Angkatan Darat dan PKI memiliki tujuan yang berbeda. Presiden Soekarno turun sebagai kekuatan penyeimbang di antara persaingan tersebut untuk menjaga agar konsep demokrasi terpimpinnya dan nasakom tetap berjalan. Tetapi tidak berhasil karena adanya upaya PKI melalui Gestapu untuk menyingkir Angkatan Darat. Namun pada saat itu, Angkatan Darat lebih siap menghadapinya. Hal itu justru menyebabkan demokrasi terpimpin gagal dan Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan (Budiardjo, 1998).
Menurut Herbert Feith, pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Indonesia, pada awa 1970an itu dimotori negara, bukan oleh masyarakat. Negara memiliki peran yang sangat besar, mulai dari tahap perencanaan sampai pada implementasi pembangunan ekonomi. Arah pembangunan ekonomi yang dipilih Herbert Feith adalah sistem kapitalisme, dengan cara meniru negara-negara kapitalisme maju, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat (developed countries). Dalam rangka membangun ekonomi kapitalistik ini, negara berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan transnasional. Bersamaan dengan pembangunan ekonomi, negara juga membangun bidang politik, yang dikonsepsikannya sebagai stabilitas politik.
Diasumsikan, bahwa stabilitas politik adalah prasyarat imperatif bagi kelancaran pembangunan ekonomi. Untuk bisa mewujudkan stabilitas politik, negara melakukan berbagai tindakan represif dan koersif bagi siapa pun yang dipersepsikan atau dianggap bisa mengganggu keamanan negara dan jalannya pembangunan ekonomi.
Strategi pembangunan ekonomi yang memprasyaratkan stabilitas politik melalui tindakan “kekerasan” itu oleh Feith disebut sebagai rezim pembangunan yang represif (represive developmental rezim). Ciri-cirinya adalah pemerintahan pada berbagai level – mulai dari level atas atau pusat sampai ke tingkat bawah, daerah – melibatkan kaum militer. Lalu pembangunan ekonomi diatur oleh para teknokrat dan elit birokrasi dengan sistem perecanaan terpusat. Kemudian lembaga-lembaga demokrasi yang konvensional – seperti partai politik, legislatif, serta kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat, kelompok sipil – dibatasi ruang gerak dan kegiatannya (Feith, 1984). Namun di sektor politik di negara ini tidak terjadi perubahan yang signifikan.
Menurut Mochtar Mas’oed, negara tetap menyingkirkan dan meredam berbagai aktivitas kekuatan-kekuatan sipil dan politik yang kritis. Saluran dan akses politik berbagai organisasi massa ditutup. Kalaupun diberi ruang, digunakan mekanisme korporatis untuk mengkooptasi dan mengontrol dan meredam munculnya kekuatan-kekuatan civil society.
Pemilu memang dilaksanakan secara prosedural. Tetapi partai-partai telah dikebiri terlebih dahulu dengan penyederhanaan jumlah partai menjadi tiga saja. Serta upaya terus menerus untuk mengintervensi proses suksesi kepemimpinan tidak hanya di dalam partai, bahkan terhadap ormas dengan kekuatan besar. Selain itu, produk pemilu – berupa anggota DPR – secara komposisi hanya mencerminkan 50% bkekuatan dalam lembaga tertinggi (MPR). Itupun dengan catatan 60% lebih anggota DPR berasal dari Partai Golkar sebagai partai pemerintah. Dalam hitung-hitungan maksimal anggota MPR yang beroposisi hanya 20%. Sehingga secara sistemik Orde Baru berhasil melanggengkan kekuasaaanya selama lebih dari 30 tahun.
Demokrasi Sebagai Alat dan Tujuan
Eduard Bernstein, salah seorang ideolog Partai Sosial Demokratik Jerman dengan apik mendalilkan perlunya demokrasi dijalankan sebagai alat dan tujuan, sekaligus sebagai analisis historis atas perkembangan paham sosialisme agar terus dapat bertahan sebagai salah satu varian yang masih berada dalam cluster demokrasi.
Eduard Bernstein juga percaya bahwa demokrasi adalah jalan terbaik yang membuat sosialisme lebih berpengaruh dari pada sebelumnya. Akan tetapi demokrasi yang dia maksud di sini adalah terkait dengan substansi. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ketiadaan institusi yang demokratis atau tradisi demokrasi akan membuat doktrin-doktrin sosialisme menjadi kenyataan.
Kita telah terbiasa dengan istilah demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Keduanya merupakan sebuah kontinuitas dari sebuah sirkulasi prosedural dan tatanan politik yang sistematik dan bertujuan. Demokrasi sejatinya menghubungkan rakyat dengan kekuasaan yang ada ditangannya sendiri sebagai jaminan kebebasan, kesederajatan dan keadilan untuk dirinya yang harus terpenuhi. Proses pelembagaan demokrasi lah yang menghasilkan apa yang namanya lembaga kekuasaan sebagai mandatorial semata.
Partai merupakan alat untuk mencapai kekuasaan secara demokratik lewat pemilu. Partai dan produk-produk kelembagan politik lain yang dihasilkan menjadi alat untuk mencapai tujuan. Sehingga demokrasi harus konsisten dijalankan sebagai alat dan tujuan sekaligus. Tantangannya adalah alat-alat yang merupakan media mandatorial untuk merepresentasikan kehendak sehingga mereka mendapat legitimasi dan otoritas dalam memproses kerja-kerja kekuasaan lepas dari tujuan rakyat itu sendiri. Pengalaman seperti inilah yang merangkum peristiwa-peristiwa traumatik karena terpisahnya demokrasi sebagai alat dengan demokrasi sebagai tujuan atau terlepasnya kontinuitas antara demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial.
Tentang Penulis: Ahmad Mustakim, S.PdI. Aktivis demokrasi. Pernah menjadi Relawan Demokrasi, Anggota PPK Ngawen 2018, Panwascam Ngawen 2020. Menjadi jurnalis sejak 2018 hingga 2023 dan tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Blora.
*Opini di atas merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab Bloranews.com.